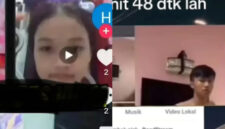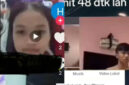DI kampungku, dulu, ada sebuah ungkapan yang mencerminkan sulitnya keadaan, yakni: “membeli beras”. Jika ungkapan itu terdengar, pertanda ada yang tak beres.
“Anak banyak, penghasilan tak tetap, dan harus membeli beras pula,” begitu orang menggambarkan nasib sangsai, dan yang menarik, situasi itu memiliki keterhubungan yang jelas dengan beras!
Baca juga: Dendang Membara Pirin Bana
Kenapa beras? Tentu saja, karena itu kebutuhan dasar paling riil, harus ada setiap hari. Anda boleh berslogan keanekaragaman pangan, tapi yang namanya beras tetap tak tergantikan. Makan tanpa lauk masih mungkin, asal ada nasi, kami bisa “makan dengan garam”. Karena itu saya suka judul novel Suparto Brata, Tak Ada Nasi Lain, nasi yang bersumber dari beras. Aneh jika belakangan ada kampanye yang minta warga mengurangi konsumsi beras. Bahkan seorang pejabat tinggi pernah minta rakyat mengurangi makan nasi. Itu bukan saja memisahkan rakyat dari kebutuhan pokoknya sehari-hari alih-alih melegitimasi alih fungsi lahan pertanian sambil buka kran impor beras lebar-lebar.
Kembali ke kampung. Ungkapan “membeli beras” atau “mambali bareh” di kampung saya dianggap titik nadir kemiskinan. Sebab itu artinya, untuk kebutuhan pokok dan paling dasar warga harus bertransaksi lebih dulu. Dan bagi orang kampung itu tak masuk akal. Kampung saya, di bilangan bekas Bandasapuluah, tepatnya Kecamatan Sutera sekarang, sebenarnya kawasan pesisir, di tepi Samudera Indonesia, namun wilayah ini juga berada di kaki Bukit Barisan di mana hamparan sawah terbentang.
Akibatnya sawah di kampung saya tak dapat dikatakan luas sekali, namun sistem pusaka tinggi telah membuat hampir semua keluarga mendapatkan bagiannya. Sebagian yang tak punya sawah ulayat bisa tetap bersawah dengan cara menyasiah (menyewa dengan takaran padi). Tidak semua sawah pula dialiri air irigasi yang cukup, sebagian besar malah sawah tadah hujan. Namun berkat siklus yang tak putus, aktivitas bersawah tertata wajar; turun ke sawah pada musim hujan, dan bertanam semangka atau palawija pada musim kemarau. Karena turun ke sawah rata-rata hanya sekali atau dua kali setahun, maka biasanya orang kampung menyebutnya dengan “bertahun” atau “pertahunan”.
Baca juga: Resensi Buku “Cara Tuhan untuk Memperingatkan Umatnya”
Hasil panen padi jarang yang dijual, karena “menjual padi” sama saja dengan “membeli beras”; sebab memang akan begitu akhirnya. Barangsiapa yang menjual padi usai panen, maka nanti juga akan terpaksa membeli beras, dan itu tetap gejala kurang beres. Bukan berarti tak ada yang menjual padi habis panen, tapi sekedarnya, buat upah menyabit dan mengirik atau mengeluarkan sasih sawah—bagi yang menyasih. Kadang biaya panen dapat teratasi berkat kerjasama, saling sumbang tenaga; saat sawah si anu panen, maka petani lain akan ikut membantu, begitu sebaliknya. Dengan demikian, ongkos finansial dapat ditekan dan jika hasil panen katakanlah berkisar antara 25-30 karung goni, maka yang “dapat naik” ke rumah bisa sekitar 20-25 karung. Itu sudah bagus.Nah, padi yang sudah bersih itu—baik bersih dari yang hampa maupun bersih dari biaya-biaya—akan dinaikkan ke atas rumah. Umumnya rumah waktu itu masih rumah kayu berlantai papan, atau rumah batu (beton) tapi ada bagian dapur atau belakang yang disediakan sebagai tempat meletakkan padi-padi itu. Maklumlah, di daerah pesisir bukan hanya bentuk rumah gadang yang tidak seperti di darek, juga keberadaan rangkiang (lumbung padi) di halaman tak begitu lazim. Maka lumbung padi secara tak langsung berada di bagian rumah yang tadi disebutkan.
Baca juga: Jambau TerakhirBiasanya padi itu dialasi tikar lebih dulu, kemudian ditutupi lagi dengan tikar pandan di bagian atasnya. Ruang di atas tikar itu masih bisa dimanfaatkan penghuni rumah untuk sekedar tempat duduk, mengaso, bahkan jadi ruang tidur. Hawa di atasnya nyaman dan hangat. Saya adik-beradik biasa memeram buah-buahan yang masih bangkar (tua, tapi belum masak) di dalam padi yang terhampar itu, seperti ambacang, mangga atau alpukat.Apabila beras terakhir dalam ketiding (tempat beras) habis, orang tua kami tinggal mengambil beberapa sukat padi di balik tikar itu, lalu dijemur di halaman. Kami menjaganya dari serbuan ayam-ayam. Menjelang petang, padi yang dijemur diangkat abak atau amak, lalu kami diminta membawanya dengan sepeda ke heler (mesin gilingan padi) yang ada di batas kampung. Waktu itu heler bisa dihitung dengan jari—heler Mak Haji Oran, heler Suli dan heler Buyung, dan itu menjadi pusat peredaran beras di kampung.
Saat mesin heler bekerja—dengan suasana dan aroma yang khas—tak lupa kami mengambil dedak padi untuk pakan ayam atau itik piaraan. Masa itu, bukan hanya hewan piaraan yang dapat makan dari dedak padi, tapi kami sehari-hari juga makan dari beras yang ditumbuk dari padi simpanan sendiri. Saking menyatunya siklus itu dalam hidup kami, membuat kami benar-benar tak pernah memikirkan soal nasi, apalagi berpikir membeli beras.
Baca juga: Sembilu Menyayat HatiBertahun-tahun kemudian, ketika saya bertemu quate Eduard Douwes Dekker alias Multatuli, saya membenarkannya karena pernah merasakan,”Kita bergembira bukan karena menuai padi; kita bergembira karena menuai padi di sawah kita.”
***
DEMIKIANLAH, hasil “pertahunan” di kampung dapat memenuhi kebutuhan dasar tiap keluarga untuk setahun lamanya atau sampai masa panen berikutnya. Perhitungan itu pas, jarang meleset, kecuali kalau terjadi hal-hal di luar dugaan, seperti kemarau panjang atau serbuan hama wereng alias pianggang. Tapi itu jarang, dan jika terjadi, maka orang akan ramai berkeluh-kesah,”Ah, sulit hidup sekarang, terpaksa kita membeli beras!” Itu artinya, membeli beras bukan hanya berat, tapi juga menyatakan keadaan yang benar-benar gawat.
Baca juga: Dualisme Kepemimpinan KAN Surantih, Camat Sutera Dinilai OffsideBisa pula perhitungan melesat karena ada saja satu-dua keluarga yang terpaksa menjual padinya, misalnya kebutuhan mendadak anak masuk sekolah atau ada yang sakit. Itu juga akan memunculkan rasa yang sama berat, bahwa menjual padi sama tak mengenakkannya dengan membeli beras. Untuk menunjukkan betapa beratnya perjuangan menyekolahkan anak misalnya, ada saja orang menyebut,”Untuk menyekolahkan si anak, sampai menjual padi orang tuanya, dan sekarang mereka hidup membeli beras!” Tapi itu masih untung karena menyangkut hal-ihwal pendidikan.
Apapun, dulu, menjual padi dan akhirnya membeli beras seolah “pantangan” yang tak boleh dilanggar. Meskipun banyak di antara warga yang juga berprofesi sebagai pelaut, atau profesi lainnya, namun biasanya mereka tetap punya sawah atau disewa untuk digarap, yang membuatnya, sekalipun nelayan, bisa ikut “bertahun”. Itu sebaik-baik rezeki, bisa bertahun sambil terus ke laut; biaya bisa diupah dari uang hasil melaut, dan hasil pertahunan nanti dapat disimpan untuk kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Tak ada lagi yang lebih enak hidup begini, Sanak.
Baca juga: Diserbu Warga, Ini Keterangan Pihak Nagari SurantihApa yang saya ceritakan ini tentu saja berbau nostalgia. Masa lalu yang mungkin akan dianggap klangenan karena penduduk sekarang sudah banyak, lahan makin habis untuk perumahan dan profesi orang kampung juga kian beragam. Akan tetapi jika dipikir-pikir, ungkapan “membeli beras” itu saya kira tetap relevan sebagai keluhan yang memberatkan, terutama di kalangan petani atau warga kebanyakan. Bagi yang berprofesi/berstatus ASN seperti guru atau perawat, mohon dimaknai secara simbolik. Setidaknya, saya masih sering mendengar ungkapan itu untuk menunjukkan keadaan diri yang hidup susah. Beberapa kali pulang kampung, atau berkontak dengan kawan-kawan, saya masih mendengar ungkapan itu sebagai saudara kembar kesusahan.“Susah sekarang, Dal, apa-apa mahal,” sebut mereka, sebagai misal. Sampai di sini masih datar, sebab hal itu memang langsung dapat dirasakan di mana-mana. Klimaksnya, jika sudah sampai pada ungkapan,”Beras harus pula dibeli” maka akan terasa benar pahitnya hidup.
Baca juga: Sehimpun Puisi Sri JumainiBagaimana kita memaknai ini sekarang? Apakah hanya cukup dianggap sebagai klangenan? Tidakkah kita bisa bertolak dari sini untuk merumuskan keadaan? Bahwa daerah kita sejatinya adalah daerah agraris, dengan sawah dan ladang, di antara laut luas membentang; sebagian besar petani penggarap, di samping sejumlah profesi lain; tapi bagaimana keadaan lahan-lahan pertanian itu kini?Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan 2016, luas lahan sawah di Pessel mencapai 30.710,0 hk. Disebutkan pula bahwa lahan sawah di daerah ini merupakan lahan sawah irigasi yang ditanami padi sampai tiga kali setahun. Dalam Tabel 2 tentang Luas Lahan Sawah Irigasi Menurut Kecamatan (2016: 14), di Kecamatan Sutera terdapat sawah terluas yang ditanami padi tiga kali setahun, yakni 1400 ha. Sisanya, 98,0 hk ditanami dua kali setahun. Di dalam tabel tersebut penanaman padi sekali setahun kosong atau tidak ada.
Baca juga: Maubek Pasie, Tolak Balanya Masyarakat Pesisir Pantai SurantihKalau tabel tersebut merujuk kawasan “mudiak” Surantiah seperti Koto Nan Tigo, mungkin benar sebab Irigasi Batang Surantih yang diresmikan Ir. Sutami sekitar tahun 70-an lalu memang memadai. Tapi di Taratak-Lansano, tempat yang saya ceritakan dalam tulisan ini, turun ke sawah lebih sering sekali setahun, hanya sesekali saja bisa dua kali setahun. Itu karena kendala pengairan. Irigasi tidak mencukupi. Belakangan dibangun irigasi Timbulun, namun masih belum banyak membawa perubahan.Jelas irigasi masih jadi kendala. Program embung yang pernah dibangun cukup banyak di sekitar Sutera, apakah benar-benar membawa untung atau justru membendung mata air menjadi mati suri? Di beberapa titik saya temui ada embung yang terbengkalai, atau dibiarkan tak berfungsi. Sebagian petani mengeluh itu tak banyak membantu atau justru merusak siklus pengairan yang sudah ada.
Baca juga: Kuliner Khas Pesisir Selatan
Di sisi lain, ada fenomena baru yang terus berulang sekarang. Seusai panen, orang memutuskan menjual padinya sebanyak-banyaknya, bahkan sampai tandas. Itu untuk berbagai kebutuhan yang kian bertambah dan biaya hidup yang terus meninggi. Tentu saja menjual padi saat panen raya membuat harga turun bahkan anjlok. Akibatnya bukan untung yang didapat, tapi buntung berkali lipat. Padi habis, uang terpakai, dan beras harus pula dibeli. Apakah ada pihak terkait seperti Bulog atau Dinas Pertanian yang mencoba mengatasi ini, dengan tawaran program yang nyata?
Saya juga bertemu orang yang punya niat untuk ikut “bertahun”, tapi keluarganya tak punya sawah warisan. Biasanya orang seperti ini bisa menyewa (manyasiah) sawah orang, seperti masa dulu hal yang jamak begitu. Tapi persoalannya, kata anak muda itu, sebut saja Rikal Sikumbang,”Orang yang punya sawah kini minta sasiah di muko.”Artinya, kalau ingin menyasiah sawah, maka sewanya harus dibayar di muka (bayar dulu) dan itu juga dengan nilai yang sudah sangat tinggi. Dulu, sasiah boleh dibayar belakangan, setelah panen. Nah, siapakah yang bisa memfasilitasi hasrat anak muda seperti ini? Apakah pemerintah setempat, mulai bupati, camat atau wali nagari, punya program pemodalan bagi mereka yang ingin menyasih sawah misalnya?Jika jawaban untuk pertanyaan sederhana ini saja belum tersedia, sampai kapan pun ungkapan “membeli beras” akan jadi cermin buram keadaan. Ibarat pepatah,”Beban berat singguluang batu.”
Raudal Tanjung Banua, sastrawan asal Pesisir Selatan, tinggal di Yogyakarta
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT